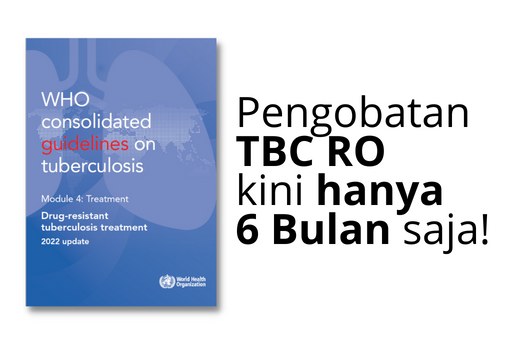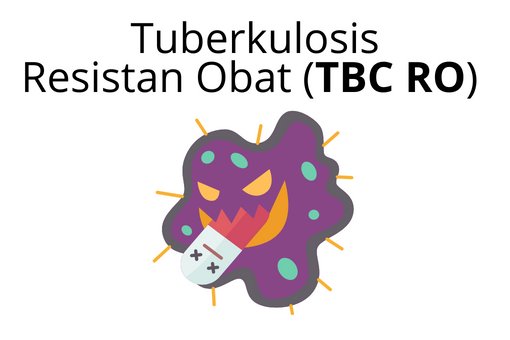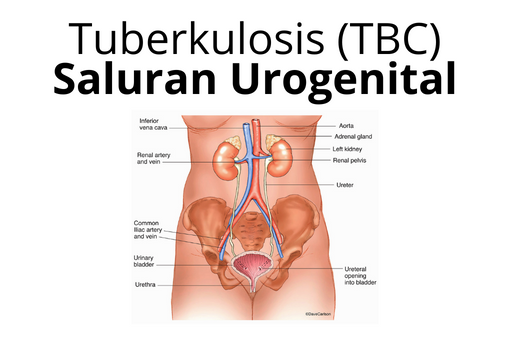Hari Kasih Sayang
18 February 2020

Februari tahun 2018 adalah bulan yang mengubah hidup saya. Di bulan itu, saya jatuh sakit dalam perjalanan ke Amerika, ke Boston dan New York. Setiba di Amerika, saya mengunjungi sahabat lama Dee Senaratne, mantan Head Of Research CLSA Indonesia yang sedang mengambil Master in Public Administration di Kennedy School, Universitas Harvard di kota Boston.
Saat di Boston itu saya jatuh sakit. Tiba-tiba menggigil luar biasa karena panas yang yang tinggi. Dikasih obat demam, panas pun sempat turun. Tapi ternyata balik lagi dengan lebih dahsyat. Begitu dahsyatnya sampai-sampai saya harus langsung masuk rumah sakit begitu tiba di New York.
Awalnya dipikir flu. Ternyata hasil tes negatif. Malaria dan DB juga bukan. Singkat cerita, akhirnya ketahuan saya terkena kombinasi serangan virus chikungunya dan satu jenis superbuglangka. Akibatnya saya pun harus dirawat inap selama dua minggu di rumah sakit Mount Sinai di New York.
Kerja keras, kualitas, dan perhatian para dokter dan perawat di Mount Sinai Hospital membantu saya untuk melewati kondisi yang sempat kritis, yang dalam bahasa medisnya disebut sebagai sepsis. Dalam kondisi ini, tubuh kita merilis zat kimia ke aliran darah untuk memerangi infeksi. Ada perang besar di tubuh dalam kondisi ini.
Untungnya asuransi kesehatan baru saya perpanjang seminggu sebelum perjalanan ke Amerika, setelah sempat pikir-pikir apakah ada gunanya setelah bertahun-tahun tidak pernah ada klaim. Biaya sakit di Amerika ternyata super mahal. Jangan sampai sakit di sana tanpa punya asuransi kesehatan yang memadai.
Pengalaman sakit itu menjadi pemicu banyak hal dalam hidup saya. Misalnya menjadi pemicu saya untuk MENCOBA menjadi orang yang lebih baik. Dan pemicu untuk mulai menulis blog ini. Juga saya jadi paham rasanya sakit dan melewati masa kritis. Apalagi melewati masa kritisnya sendirian karena saya memang tidak memberitahu keluarga di rumah, khawatir membuat mereka panik. Toh tanpa visa Amerika di tangan, keluarga tidak dapat berbuat banyak. Mendingan sekalian nggak tahu dulu sampai masa kritis terlewati. Begitu kurang lebih pemikiran saya.
Soal sakit kritis dan sendirian tanpa siapa-siapa, barusan saya memperingati dua tahun kejadian di New York dengan mampir ke Yayasan KNCV Indonesia. Pas di hari Valentine pula, di kantor mereka di Sunter, Jakarta. Yayasan KNCV Indonesia ini adalah yayasan yang mempromosikan cinta, komitmen kemanusiaan, dan kepedulian bagi penderita tuberkulosis (TBC). Misi mereka adalah eliminasi TBC dan penyakit terkait lainnya di Indonesia.
Berbicara dengan aktivis-aktivis muda di Yayasan KNCV Indonesia, saya jadi paham bahwa TBC ini bukan penyakit yang sudah tereliminasi dari bumi Indonesia. Setiap tahun, ada 316 kasus TBC tiap 100 ribu penduduk Indonesia, atau 800.000-an kasus TBC per tahun. Menurut data WHO, di tahun 2018 ada 845.000 kasus TBC di Indonesia! Jumlah yang sangat besar. (Bahkan di negara maju seperti Korea Selatan, TBC masih menjadi momok. Yang nonton film Korea Parasite, pemenang 4 Academy Awards 2020 termasuk film dan sutradara terbaik, pasti paham soal ini).
Dan TBC adalah penyakit yang sangat mengerikan, walaupun bisa diobati. Kuman TBC dapat menjadi resisten obat (TBC-RO) kalau pasien tidak menyelesaikan pengobatan TBC sampai tuntas atau petugas kesehatan memberikan pengobatan yang tidak tepat, baik paduan, dosis, lama pengobatan maupun kualitas obatnya. Masalahnya, kalau sudah menjadi TBC-RO biaya pengobatan melambung tinggi, yaitu US$ 4.440 per kasus vs. US$ 159 untuk TBC biasa.
Walau Pemerintah Indonesia menyediakan obatnya secara cuma-cuma, komitmen yang dibutuhkan dari pasien TBC RO tetap luar biasa berat. Pengobatan harus dilakukan tiap hari dan masa pengobatan lama, yaitu 20-24 bulan dengan disuntik tiap hari selama enam bulan. Jarak rumah sakit atau klinik juga sering lumayan jauh, artinya pasien harus meninggalkan pekerjaan. Efek samping obat juga sangat berat. Selain mual, muntah, sakit kepala, diare, dan lemas, efek samping yang lain adalah nyeri sendi, telinga berdenging, kulit menghitam, berat badan turun drastis, depresi dan bahkan halusinasi.
Beberapa Kisah Penderita TBC
Dari pertemuan di hari Valentine dengan aktivis-aktivis hebat Yayasan KNCV Indonesia, saya mendengar banyak cerita mengharukan penderita TBC.
Kisah Dewi dari Bandung misalnya. Terkena TBC di tahun 2007, dokter rumah sakit sempat menyatakan Dewi meninggal dunia. Tapi Dewi masih diberi kesempatan untuk hidup dan menerima pengobatan. Sayangnya, Dewi harus dinyatakan positif sakit TBC-RO di tahun 2010 dan harus ke Jakarta untuk berobat. Karena kondisi ekonomi, terpaksa Dewi harus menunggu hingga 2012 untuk menjalani pengobatan TBC-RO di Bandung. Lagi-lagi, Dewi merasa malaikat maut telah datang menjemput. Yang dia lakukan adalah menolak memejamkan mata karena takut tidak pernah bangun lagi dari tidurnya.
Demi berobat, Dewi harus meninggalkan pekerjaanya sebagai kasir. Dan mulai merasakan efek samping pengobatan TBC-RO. Mual, rambut rontok, penglihatan menjadi buram, dan tergantung pada oksigen. Berat badan turun drastis ke 32 kg, asam urat naik drastis sampai-sampai kaki tidak bisa ditekuk.
Yang tragis, memasuki bulan keempat bergelut melawan TBC-RO, suami Dewi yang menjadi pilar dukungan moralnya malah menghilang. Untungnya kedua orang tua Dewi mendukung penuh. Suami yang menghilang menjadi pemacu Dewi untuk sembuh dan membuktikan kepada suaminya. Dewi sembuh dari TBC-RO di bulan November tahun 2013 dan sekarang menjadi aktivis pemberantasan TBC.
Soal kisah ditinggal suami sewaktu berjuang hidup mati melawan TBC-RO juga dialami oleh penderita TBC-RO di Tanah Karo: Ayu Mayasari. Terinfeksi TBC-RO di tahun 2015, Ayu harus mulai proses pengobatan di Medan dengan menjalani rawat inap selama sebulan. Efek samping obat pun ia rasakan, mual, muntah, gelisah.
Tapi yang paling bikin Ayu gelisah adalah sang suami yang malah memilih pulang ke Tanah Karo, meninggalkan Ayu di Medan. Keluarga pun membawa Ayu menemui suami di kampung. Sesampainya di sana, Ayu dan keluarga datang ke rumah kontrakan suami. Sepertinya suami mendengar suara Ayu dan keluarga datang dan melarikan diri. Pintu tidak terkunci, TV dan kran air juga masih menyala. Tidak mungkin bila ia pergi tidak mengunci pintu dan mematikan TV dan air. Ayu menunggu sampai jam 4 sore dan sang suami tidak pulang.
Ada juga kisah penderita TBC yang diperlakukan buruk oleh petugas rumah sakit. Misalnya kipas angin besar diarahkan ke pasien dan akhirnya diusir. Karena tidak tahu bahwa TBC-RO bisa disembuhkan.
Saya bisa sangat relate dengan kisah sedih penderita TBC-RO tersebut, terlebih setelah apa yang saya alami, sakit di New York. Kebayang sedihnya. Dan putus asanya.
Peran Anak Muda Pegiat TBC
Dan pertemuan di hari Valentine dengan aktivis pemberantasan TBC di Yayasan KNCV Indonesia sungguh membesarkan hati saya. Kisah dua dokter muda, Yeremia Prawiro Mozart Runtu dan Angelin Yuvensia misalnya. Keduanya dokter lulusan perguruan tinggi ternama di Indonesia. Yeremia lulusan kedokteran Universitas Brawijaya Malang dan Angelin lulusan kedokteran Universitas indonesia.
Waktu masuk fakultas kedokteran, Yeremia maupun Angelin berpikir suatu hari akan jadi dokter spesialis, dengan penghasilan sangat menarik. Tapi di tengah jalan, keduanya mau berfokus pada tujuan yang lebih besar, bigger purpose. Dengan tidak mengurangi rasa hormat pada rekan-rekan dokter yang ingin menjadi dokter spesialis, kedua dokter muda ini merasa bisa melayani masyarakat dalam skala yang jauh lebih besar lewat pelayanan kesehatan masyarakat (public health) seperti melalui Yayasan KNCV Indonesia ini.
Tentu pengorbanan, dari segi opportunity costuntuk keduanya, begitu besar. Penghasilan seorang dokter spesialis bisa berkali lipat dokter technical officer di Yayasan KNCV Indonesia. Dan dokter di Yayasan KNCV Indonesia tidak diperbolehkan menambah penghasilan dengan berpraktek. Ini merupakan aturan organisasi. Tujuannya supaya ada fokus penuh ke misi bebas TBC di Indonesia.
Yeremia yang kelahiran Malang sudah 3 tahun mengabdi di Yayasan KNCV Indonesia. Ayah Yeremia yang dokter spesialis di Surabaya tidak keberatan anaknya ingin mengabdi memerangi TBC. Sang ibu tadinya ingin Yeremia menjadi spesialis penyakit dalam yang dianggap sangat menjanjikan sebagai pilihan karir. Tapi melihat sendiri bagaimana Yeremia menjadi berkat bagi begitu banyak pasien TBC yang menderita, sang ibu pun akhirnya mendukung penuh pilihan Yeremia.
Bagi Angelin, jalan hidupnya berubah ketika sedang menjalani tugas penempatan ke Kabupaten Sikka di Flores, NTT. Ini tempat kelahiran ayahnya. Hatinya sangat tersentuh oleh kondisi kesehatan masyarakat di sana. Pernah Angelin ditugaskan ke Desa Mapitara di NTT yang super terpencil. Begitu terpencilnya sampai-sampai ia tidak membolehkan ibunya mengunjunginya. Takut disuruh pulang.
Alat-alat kesehatan bantuan pemerintah, seperti mikroskop elektron dan kursi dokter gigi, tidak dapat berfungsi karena tidak ada akses listrik. Sahabat setia Angelin selama tugas penempatan itu adalah seekor anjing bernama Teri, yang sayangnya tidak diperbolehkan dibawa ke Jakarta setelah tugas penempatan selesai. Karena ada larangan membawa keluar anjing dari Pulau Flores. Larangan ini terkait dengan adanya kasus rabies di NTT.
Melihat sendiri kondisi masyarakat di Sikka NTT, Angelin mengambil kuliah lagi di jurusan public healthdi UNSW di Sydney setelah masa tugasnya berakhir. Setelah itu bergabung ke Yayasan KNCV Indonesia.
Yeremia dan Angelin menemukan panggilan hatinya, yaitu membuat dampak positif yang besar ke masyarakat. Di satu pagi mereka bangun dari tidur, dan mengatakan pada diri mereka sendiri untuk tidak lagi takut untuk bahagia.
Tidak semua yang bekerja di Yayasan KNCV Indonesia berlatar belakang dokter.
Di hari Valentine itu, saya juga bertemu dengan Melya Findi, kelahiran Muntilan, Jawa Tengah. Latar belakangnya ilmu komunikasi dan cita-cita awalnya menjadi profesional dunia advertising. Sebagai petugas sosial, persentuhannya dengan penderita TBC di Kabupaten Keerom di Papua mengubah hidupnya. Membawanya ke YKI.
Pemahaman Melya yang dulu tidak dia miliki saat mendampingi anak yang terkena TBC di Papua membuatnya mau belajar bahwa sebagai petugas kemanusiaan, adalah hal yang sangat penting untuk belajar memahami konteks dan situasi. Kerap petugas sosial ingin membantu, tapi ternyata kurangnya pemahaman justru malah menjadi sumber masalah baru. Ini yang kemudian membuat Melya untuk mau berperan dalam membantu edukasi TBC melalui media atau sarana apapun. Agar lebih banyak yang memahami TBC. Bagi Melya, penting sekali organisasi kemanusiaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat paham akan hal ini supaya tidak salah penanganan seperti kasusnya dulu
Latar belakang ilmu komunikasinya sangat diperlukan untuk menyebarkan pesan bahaya TBC dan pada saat yang bersamaan pesan bahwa TBC ini dapat disembuhkan. Yang juga membuat Melya begitu bersemangat adalah kepedulian Presiden Jokowi pada nasib penderita TBC.
Juga saya bertemu dengan Erman Varella. Bukan orang Italia. Dia orang Padang. Jago bikin rendang. Dan pintar berdagang pula, ditunjang dengan latar belakang sekolah akuntansi. Sampai suatu hari Erman sakit autoimun, divonis oleh dokter hidupnya tinggal beberapa bulan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Erman sembuh dan memutuskan untuk melakukan lompatan, atau jump. Awalnya sebagai aktivis pasien HIV, kemudian belakangan bergabung ke Yayasan KNCV Indonesia untuk membantu penderita TBC. Bisnis Erman pun ditutup, 100% hidupnya untuk menemani penderita TBC. Supaya tidak lagi sendirian dan jatuh ke jurang depresi.
Hari Valentine tahun 2020 ini begitu istimewa bagi saya. Karena beberapa orang istimewa di Yayasan KNCV Indonesia bersedia berbagi cerita. Tentang bagaimana mereka akhirnya memilih untuk tidak lagi takut untuk berbahagia dan memilih karier yang bermakna bagi mereka. Tentang bagaimana mereka memilih meraih hidupnya kembali ke tangan mereka.
Juga mereka memberikan harapan buat saya, bahwa masih banyak anak muda yang lebih memilih tujuan atau purpose yang lebih besar dalam hidupnya. Apa yang mereka kerjakan di Yayasan KNCV Indonesia mungkin akan mudah terlewati karena kita mungkin berpikir TBC itu penyakit masa lalu. Ternyata salah sama sekali. Ancaman TBC di Indonesia masih begitu nyata. Pejuang-pejuang Yayasan KNCV Indonesia dan organisasi nirlaba sejenis lainnya makin terasa relevan dengan wabah Corona yang sedang melanda.
Di tengah ancaman Corona, kasus gagal bayar, perang dagang, dan begitu banyak masalah lain, kita punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah komplain secara masif. Pilihan kedua, mengambil kontrol atas hidup kita dan mengelilingi diri kita dengan orang-orang positif. Pilihan kedua memperkuat karakter kita, di tengah-tengah kondisi tersulit sekalipun. Dalam kerangka pilihan kedua ini, kita sedang mencetak building blocksuntuk pembentukan karakter kita. Yang selalu bersyukur, optimistis, dan tidak mudah panik. Yang melihat kesempatan di saat yang sulit. Yang melihat hidup ini sangat indah.
Selamat hari kasih sayang.
Ditulis oleh Wuddy Warsono CFA, 14 Februari 2020
‘In all things we should try to make ourselves be as grateful as possible. For gratitude is a good thing for ourselves in a matter in which justice, commonly held to belong to others, is not. Gratitude pays itself back in large measure.”
Artikel ini pertama kali dipublikasikan di http://sucorsekuritas.com/blog/personal/hari-kasih-sayang